
Negara Indonesia Kaya Raya, Tapi Rakyatnya Kok Miskin ?
INDONESIA kerap dipuji sebagai tanah surga. Pepatah lama menyebut, “tongkat kayu dan batu jadi tanaman.”
Faktanya, negeri ini memang dianugerahi kekayaan alam melimpah. Dari emas di Papua, batu bara di Kalimantan, minyak dan gas di Sumatera, hingga nikel di Sulawesi.
Laut yang luas menjanjikan ikan tanpa henti, hutan yang lebat menjadi paru-paru dunia, dan tanah yang subur bisa menumbuhkan apa saja.
Singkatnya, jika ukuran bangsa adalah harta alam, Indonesia termasuk salah satu yang terkaya di dunia.
Namun, mari menoleh ke wajah rakyatnya. Di tengah kabar pertumbuhan ekonomi yang naik, kita masih mendapati ibu-ibu yang harus berutang di warung untuk membeli beras.

Kita masih melihat anak-anak putus sekolah karena orangtuanya tidak sanggup menanggung biaya hidup. Kita masih menyaksikan orang sakit menunda berobat karena biaya rumah sakit lebih mahal daripada kemampuan dompetnya.
Inilah paradoks yang menyayat hati: negara kaya, tetapi rakyatnya miskin.
Secara logika sederhana, jika negara kaya, seharusnya rakyatnya sejahtera. Namun, kenyataan berkata lain. Pertanyaan yang wajar muncul adalah: jika negara kita begitu kaya, uangnya ada di mana?
Pertama, sebagian besar kekayaan alam kita diekstraksi oleh perusahaan besar, baik asing maupun domestik.
Dari tambang emas hingga minyak dan gas, kontrak kerja lebih banyak memberi keuntungan kepada pemilik modal ketimbang rakyat. Hasilnya, devisa memang masuk, tapi keuntungan terbesar tidak tinggal di negeri ini.
Kedua, kebocoran anggaran negara menjadi cerita lama yang tak pernah selesai. Laporan demi laporan menunjukkan betapa besar dana publik yang bocor lewat korupsi, mark up proyek, hingga penyalahgunaan wewenang.
Uang rakyat yang seharusnya kembali dalam bentuk sekolah, rumah sakit, atau jalan yang baik, justru lenyap di rekening segelintir orang.
Ketiga, kebijakan pembangunan kerap tidak berpihak pada mayoritas rakyat. Proyek mercusuar berdiri, infrastruktur megah dibangun, tapi tidak serta-merta menjawab kebutuhan dasar: pekerjaan layak, pendidikan bermutu, dan layanan kesehatan terjangkau.
Rakyat kecil sering hanya menjadi penonton dari “pesta” pembangunan.
Setiap tahun, pemerintah mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi. Angka itu seakan menjadi simbol keberhasilan.
Namun, pertanyaan yang patut diajukan adalah: apakah rakyat benar-benar merasakan pertumbuhan itu?
Pertumbuhan ekonomi bisa naik karena konsumsi elite atau karena investasi asing besar-besaran, tetapi jika distribusinya timpang, rakyat tetap miskin.
Seorang buruh pabrik tetap menerima upah minimum yang pas-pasan, sementara segelintir pemilik modal bisa melipatgandakan keuntungan.
Ketimpangan inilah yang membuat “pertumbuhan” lebih terasa sebagai statistik di atas kertas daripada realita di dapur rakyat.
Belakangan, rakyat kecil semakin ditekan dengan kenaikan beban pajak. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di berbagai daerah melonjak signifikan, membuat banyak warga resah.
Rumah sederhana dan lahan kecil yang mereka miliki kini dibebani tarif yang tak sepadan dengan penghasilan.
Ironisnya, di saat rakyat harus merogoh kocek lebih dalam untuk pajak, kita menyaksikan kabar kenaikan gaji para pejabat elite.
Selain itu, berbagai fasilitas mewah tetap mengalir deras: mobil dinas baru, gedung megah, perjalanan dinas ke luar negeri, hingga tunjangan fantastis. Semuanya dibiayai dari pajak rakyat.
Maka, pertanyaan itu kian tajam: untuk siapa sebenarnya negara ini dikayakan? Untuk rakyat yang membayar pajak, atau untuk segelintir elite yang menikmatinya?
Laporan ketimpangan menunjukkan bahwa segelintir orang di negeri ini menguasai kekayaan setara dengan ratusan juta rakyat.
Bayangkan: hanya sebagian kecil penduduk yang menikmati hasil terbesar dari kue pembangunan. Sementara itu, mayoritas rakyat harus puas dengan sisa-sisa yang tercecer.
Ketimpangan ini menciptakan jurang sosial yang lebar. Perumahan mewah berdiri megah dengan pagar tinggi, bersebelahan dengan kampung kumuh yang warganya kesulitan mendapatkan air bersih.
Mobil-mobil mewah melintas di jalan tol baru, sementara di gang sempit banyak anak-anak yang berlari tanpa alas kaki.
Kontradiksi semacam ini bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan bom waktu sosial. Tidak ada bangsa yang bisa terus-menerus mengabaikan ketidakadilan tanpa konsekuensi.
Kemiskinan sering digambarkan sebagai nasib yang harus diterima dengan sabar. Narasi ini berbahaya, karena membuat rakyat pasrah. Padahal, kemiskinan bukanlah takdir, melainkan hasil dari struktur yang tidak adil.
Kita kaya sumber daya, tapi salah urus. Kita punya banyak uang, tapi bocor di jalan. Kita punya anggaran besar, tapi lebih banyak tersedot untuk kepentingan segelintir elite.
Selama pola seperti ini berulang, rakyat tidak akan pernah benar-benar merasakan kekayaan negerinya sendiri.
Kemiskinan struktural berdampak luas. Pendidikan yang seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan, justru sulit dijangkau oleh mereka yang miskin.
Anak dari keluarga tak mampu sering berhenti sekolah lebih awal untuk membantu orangtua mencari nafkah. Akibatnya, mereka kesulitan meningkatkan taraf hidup di masa depan.
Di bidang kesehatan, rakyat miskin menghadapi pilihan pahit: tetap sakit atau menanggung utang demi berobat.
Meski ada program jaminan kesehatan, pelaksanaannya masih menyisakan banyak persoalan. Pada akhirnya, kesehatan menjadi hak istimewa bagi mereka yang mampu membayar.
Lapangan pekerjaan juga menjadi masalah besar. Banyak lulusan muda tidak mendapat pekerjaan sesuai keterampilan.
Sementara itu, sebagian besar kesempatan kerja yang tersedia adalah sektor informal dengan penghasilan rendah dan tanpa jaminan.
Pertanyaan “Rakyat miskin, negara kaya, uangnya di mana?” bukan sekadar retorika. Ini adalah gugatan moral kepada para penguasa, pemilik modal, dan sistem yang mengatur negeri ini.
Kekayaan negara harus kembali kepada rakyat, bukan berhenti di tangan segelintir orang. Negara tidak boleh berhenti berbangga diri pada melimpahnya sumber daya alam.
Kekayaan sejati bangsa bukan ditentukan oleh banyaknya emas di perut bumi atau besarnya cadangan minyak di laut, melainkan dari seberapa adil kekayaan itu didistribusikan.
Kita tidak membutuhkan klaim kaya, kita membutuhkan keadilan. Kita tidak butuh angka pertumbuhan ekonomi yang indah di laporan, kita butuh harga beras yang terjangkau di pasar.
Kita tidak butuh pidato tentang surplus, kita butuh pekerjaan layak dengan penghasilan yang cukup. Kita tidak butuh pajak naik di tengah beban hidup yang berat, sementara para pejabat bergelimang fasilitas mewah.
Selama rakyat masih lapar, anak-anak masih putus sekolah, dan orang sakit masih menunggu biaya berobat, klaim “negara kaya” akan terdengar hampa.
Karena itu, pertanyaan ini tidak boleh berhenti diajukan, agar menjadi pengingat sekaligus peringatan : Negara Indonesia Kaya Raya, Tapi Rakyatnya Kok Miskin ? (Muh. Siddik Ibrahim)
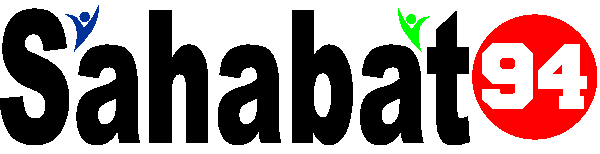




Tinggalkan Balasan